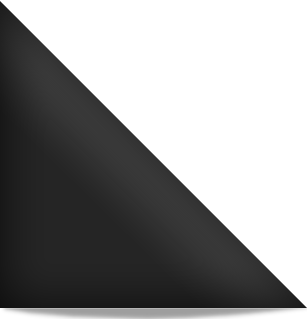Judul : Lekra Tak Membakar Buku
(Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965)
Penulis : Rhoma Dwi Aria Yuliantri & Muhidin M Dahlan
Penerbit : Merakesumba
Cetakan : I, Sept 2008
Tebal : 584 hlm ; 15x24 cm
Jika kita mendengar kata Lekra, maka yang langsung terpikirkan oleh kita adalah sebuah lembaga kebudayaan bentukan PKI yang pernah membikin ricuh panggung budaya Indonesia di era Demokrasi Terpimpin (1950-1965), tukang ganyang, pembuat onar, pemicu konflik tak berkesudahan dengan para sastrawan Manifes Kebudayaan (Manikebu), dan telibat pembakaran buku-buku di depan Kantor USIS (Pusat Informasi Amerika)
Stigma negatif yang ditempelkan pada Lekra ini terus melekat dalam benak kita dan keterlibatan Lekra dalam pembakaran buku yang sebenarnya tak terbuktikan itu telah menjadi mitos abadi karena hal ini terus ditulis di berbagai media dan dikisahkan oleh para sastrawan-sastrawan senior penandatangan Manifestasi Kebudayaan ketika menggambarkan situasi politik dan budaya Indonesia di tahun 50-60an
Mitos tersebut seolah tak terbantahkan karena suara-suara mantan aktifis Lekra yang menyangkalnya telah dibungkam ketika penguasa orde baru ‘menjahit’ mulut para lawan-lawan politiknya. Tak hanya itu, secara sengaja sejarah dan kiprah Lekra di ranah budaya Indonesia dikerdilkan hingga yang tercatat sekedar pertarungan antara dua kubu dalam isu kesusasteraan nasional : Lekra vs Manikebu.
Lalu apa dan bagaimana sesungguhnya Lekra ? Apa saja yang telah dikerjakannya selama lembaga kebudayaan ini menguasai panggung budaya Indonesia selama lima belas tahun (1950-1965)?. Tak banyak yang mengetahuinya karena tak satu bukupun yang secara komprehensif pernah menulis tentang Lekra hingga akhirnya terbitlah buku bertajuk “Lekra Tak Membakar Buku” karya Muhidin M Dahlan dan Rhoma Dwi Aria Yuliantri.
Buku ini bisa dikatakan buku yang paling komprhensif mengenai Lekra yang disusun secara sistematis dalam sepuluh bab plus daftar singkatan /akronim, lampiran, dan indeks. Dimulai dari bab Mukadimah yang mencatat situasi menjelang Kongres I Lekra (1959) ketika seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus segaris dengan Manifestasi Politik (Manipol)-nya Soekarno. Demikian pula dengan sikap berkebudayaan yang arahnya sudah jelas : “Seni untuk Rakyat” dan “politik adalah panglima kebudayaan”. Dalam Konggres-nya inilah Lekra mencoba merumuskan berbagai aksi nyata di lapangan kebudayaan yang memihak Rakyat, anti imperialis, dan anti feodal!
Masih dalam bab yang sama, diungkapkan pula kelahiran dan peran Lekra secara umum sebelum dibahas secara detail di bab-bab berikutnya. Satu hal yang menarik adalah terungkapnya bahwa Lekra bukanlah salah satu organ PKI seperti yang selama ini banyak diasumsikan orang. Hal ini tampak saat diselenggarakannya Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner (KSSR) yang sepenuhnya dilakukan oleh PKI. Memang dalam kenyatannya banyak seniman-seniman Lekra ikut terlibat , namun kapasitas mereka sebagai seniman “progresif revolusioner” dan bukan sebagai Lekra secara institusi. Jika Lekra memang organ resmi PKI tentu saja konferensi ini akan dilaksanakan oleh Lekra sebagai lembaga kebudayaan yang paling siap dan kompeten untuk menyelenggarakannya, atau setidaknya nama Lekra akan selalu disebut-sebut. Pada kenyataannya hingga resolusi KSSR diumumkan, Lekra tak pernah disebutkan sebagai bagian dari PKI.
Karena itulah buku ini menyebutkan secara gamblang bahwa : “
Lekra tak pernah menjadi underbow PKI. Lekra adalah organisasi merdeka yang tak masuk dalam kendali komando PKI…Walau tak bisa dipungkiri bahwa banyak pekerja budaya komunis yang menjadi anggota Lekra di pucuk-pucuk pimpinannya. “ (hal 61).“Menyebut Lekra bersih sama sekali dari pengaruh PKI adalah kesalahan fatal, tetapi menyebutnya menginduk kepada PKI juga keliru. Lebih tepat hubungan itu adalah hubungan kekeluargaan ideologi..(hal 63)Selain itu terungkap pula bahwa Pramoedya Ananta Toer bukanlah komunis. Hal ini terungkap ketika PKI hendak melakukan “pemerahan total” pada Lekra melalui konggres KSSR .
“..bahkan Nyoto yang pendiri Lekra pun menolak “pemerahan total“ Lekra dengan pertimbangan hengkangnya tenaga-tenaga potensial Lekra yang non-Komunis seperti Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tatang Sontani, dan sebagainya.” (hal 62)Setelah bab Mukadimah, buku ini membahas mengenai Riwayat Harian Rakjat yang merupakan terompet PKI dan Koran politik nasional terbesar pada masanya, dan tempat dimana sastrawan-sastrawan Lekra mengisi secara penuh lembar-lembar kebudayaannya yang merupakan sumber utama dari lahirnya buku ini.
Kemudian mulailah buku ini membahas semua kerja Lekra dan pemikiran-pemikiran seniman Lekra diberbagai bidang kebudayaan yang dibagi secara bab per bab mulai dari sastra, film, seni rupa, seni pertunjukan, seni tari, musik, dan buku. Dari berbagai bahasan dalam buku ini akan terlihat bahwa para Lekra sangat militan dalam melaksanakan kerja budaya yang segaris dengan prinsip Manipol yang menentang kebudayaan imperialis dan sepenuhnya memihak sekaligus memberdayakan kebudayaan Rakyat. Di tangan Lekra beberapa seni dan kebudayaan rakyat yang telah terkurung dalam kebudayaan feodal ( wayang, tari-tarian keraton, dll) yang tadinya hanya dipentaskan di kalangan dan tempat-tempat tertentu, kini dikembalikan pada rakyat sehingga semua rakyat bisa menikmati dan mengembangkannya.
Lekra juga membabat habis semua bacaan-bacaan, film, musik yang tidak sesuai dengan garis kebijakan Manipol termasuk karya-karya sastrawan Manikebu. Sebagai gantinya, Lekra menumbuh kembangkan bacaan, film, dan musik yang sesuai dengan jiwa revolusioner. Dalam berbagai simposium kebudayaannya Lekra mencatat dan menginventarisir semua kesenian-kesenian rakyat dan mengurus hak ciptanya. Kalau saja apa yang dikerjakan Lekra tak terkubur oleh sebuah prahara politik di tahun 65 mungkin kini tak ada ceritanya kalau kesenian reog ponorogo, dan beberapa lagu daerah diklaim sebagai milik budaya negara tetangga kita.
Dalam bidang musik, selain mengecam musik ngak-ngik-ngok yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian nasional, Lekra juga sangat prihatin terhadap perilaku anak-anak kecil yang menyanyikan lagu-lagu dewasa yang liriknya cengeng dan cinta-cintaan. Karenanya Lekra membahasnya secara khusus dalam Konferensi Lembaga Musik Indonesia (LMI/Lekra). Kondisi ini tampaknya tak jauh berbeda dengan keadaan sekarang dimana anak-anak tak memiliki lagu-lagu yang sesuai dengan usia mereka sehingga tak heran kalau kita mendengar anak-anak menyanyikan lagu –lagu cinta orang dewasa.
Di bidang buku, kita akan melihat bagaimana saat itu pameran-pameran buku tak sekedar ajang bisnis semata, melainkan menjadi ajang propaganda politik melalui buku-buku yang dipamerkan. Secara menarik kita akan diajak melihat siapa-siapa saja yang ikut dalam pemeran buku yang saat itu bernama “Gelanggang Buku” dan buku-buku apa saja yang dipamerkan. Hal ini mungkin bisa berguna bagi penyelenggara pameran buku di masa kini yang umumnya hanya memindahkan aktifitas toko buku ke dalam pameran.
Kemudian dibahas pula politik sebagai panglima buku, politik buku pelajaran, lembaga penerbitan buku Lekra, dan bab khusus “Lekra tak membakar buku” yang berisi fakta-fakta bahwa Lekra tak pernah membakar buku dan melarang peredaran buku-buku yang notabene adalah wewenang Kejaksaan Agung. Berdasarkan guntingan-guntingan Koran Harian Rakjat yang menjadi dasar buku ini, kedua penulis buku ini sampai pada kesimpulan bahwa
“tak satupun individu yang menyebutkan bahwa Lekra secara keorganisasian maupun individu-individu ikut serta dalam pembakaran buku” (hal 476)
Masih banyak sepak terjang Lekra yang akan kita dapat di buku ini. Pada intinya buku ini memang mengupas habis kerja-kerja kreatif yang dihasilkan Lekra selama 15 tahun (1950-1965) di bidang kebudayaan sebelum lembaga ini dibekukan dan seluruh kegiatannya dihapus dari memori dan sejarah bangsa Indonesia.
Kini kita patut bersyukur, karena kiprah Lekra yang telah dengan sengaja dihilangkan dari sejarah bangsa ini kembali terkuak dan dapat dibaca oleh semua orang. Ini semua berkat ‘kegilaan’ dua penulis muda yang dengan tekun menyelisik sekitar 15 ribu artikel kebudayaan di Harian Rakjat selama 1.5 tahun yang tersimpan dalam ruang terlarang untuk dibaca di sebuah perpustakaan di Jogya. Artikel-arttikel itu terpaksa mereka salin karena lembar koran yang sudah usang sebagian besar sudah tak memungkinkan lagi untuk di foto copy.
Dari ribuan artikel yang mereka baca dan salin inilah mereka dan menyusunnya sehingga menjadi sebuah buku utuh yang enak dibaca, .
“Kami hanya mengatur tempo dan menggilir siapa yang naik panggung duluan dan siapa yang kena giliran berikutnya. Untuk memberi suasana dan raut wajah dan suara semasa, maka kami sebanyak mungkin mengiringi kembali seluruh bahasan dengan kutipan langsung dari potongan-potongan berita braksen ejaan lama itu?” (hal 6).
Tampaknya kegilaan ide dan ketekunan kerja yang dilakukan Muhidin dan Rhoma Dwi Aria tak sia-sia. Buku yang awalnya diprediksi oleh kedua penulisnya hanya akan setebal duaratusan halaman ternyata menggelembung menjadi hampir 600 halaman karena semakin meluasnya temuan-temuan baru yang mereka temukan untuk diungkapkan. Jangan menciut melihat ketebalannya, karena walaupun tebal dan bersumber dari ribuan artikel-artikel yang berdiri sendiri namun kedua penulis berhasil merangkainya menjadi sebuah buku yang sistematis, runut, tak bertele-tele, dan enak dibaca. Lampiran-lampiran risalah rapat, hasil komunike, struktur organisasi, dan sebagainya merupakan bonus bagi mereka yang berniat meneliti lebih dalam mengenai Lekra.
Melihat lengkapnya bahasan dalam buku ini tampaknya inilah buku tentang Lekra yang paling komprehensif yang pernah diterbitkan di Indonesia semenjak Lekra berdiri hingga kini. Namun demikian ada yang mengkritik buku ini karena hanya bersumber dari guntingan-guntingan artikel lembar kebudayaan Harian Rakjat tanpa mencari sumber lain berupa wawancara terhadap pelaku sejarah yang masih hidup atau sumber-sumber kepustakaan lain.
Selain itu, ketika saya selesai menamatkan buku ini, saya bertanya-tanya mengapa judul bukunya “Lekra tak Membakar Buku”, padahal yang dibahas lebih dari sekedar jawaban atas pernyataan tersebut. Menurut saya judul tersebut mengecilkan luasnya cakupan yang dibahas dalam buku ini.
Ketika kedua hal tersebut saya tanyakan pada salah seorang penulisnya (Muhidin M Dahlan), ia mengatakan bahwa tak adanya narasumber dari para tokoh sejarah dalam menyusun buku ini sudah disadarinya sejak awal, “Itulah kelemahan sekaligus kekuatan buku ini”, ungkapnya. Wawancara terhadap tokoh-tokoh Lekra yang masih hidup dilakukan hanya sebatas konfirmasi nama, tak bisa lebih dari itu, faktor usia tampaknya menjadi kendala karena mungkin ingatan mereka sudah tak jernih lagi.
Sedangkan untuk judul, Muhiddin menjelaskan bahwa dalam proses kreatifnya ia cenderung mengambil judul bab yang paling kuat. Selain itu bab “Lekra tak Membakar Buku” adalah yang ditulis paling awal ketika buku ini dikerjakan, dan dari bab inilah maka pembahasannya menjadi semakin berkembang.
“Tidak ada bab itu sebagai pemicunya , maka tidak akan ada buku Lekra.”, demikian imbuhnya.
Kritik lainnya untuk buku ini adalah hurufnya yang terlalu kecil dan beberapa kesalahan cetak sehingga mengganggu kenyamanan membaca. Untuk ukuran huruf mungkin ini salah satu cara untuk menyiasati agar buku ini tidak bertambah ‘gemuk’ yang tentunya akan mengakibatkan harganya menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh khalayak ramai.
Terlepas dari baik buruknya buku ini, saya berani mengatakan bahwa buku ini buku merupakan karya monumental yang mendokumentasikan penggalan sejarah berkebudayaan di Indonesia. Karenanya buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh para pecinta sejarah, pemerhati, dan pelaku gerakan kebudayan Indonesia. Kiprah Lekra selama lima belas tahun tampil apa adanya dalam buku ini. Ada yang buruk, ada pula yang baik. Yang buruk bisa menjadi pelajaran agar hal serupa tak terulang kembali. Sedangkan apa yang baik dari kerja kreatif Lekra setidaknya dapat menjadi inspirasi dan bisa dijadikan contoh dalam mengembangkan kebudayaan kita saat ini.
Yang pasti buku ini akan membuka mata kita bahwa sejarah Lekra tak sekedar berisi polemik tak berkesudahan dengan pengusung Manifes Kebudayaan. Lekra bukan hanya diisi oleh orang-orang yang haus kuasa, tukang boikot, tukang cela, dan pembuat onar panggung kebudayaan, tapi Lekra adalah sebuah lembaga kebudayaan yang telah memberi warna dan sumbangsih yang luar biasa bagi kebudayaan Indonesia sebelum tragedi nasional menumbuk dan menghancurkan semua hasil kerja keras yang dipupuk selama 15 tahun tanpa henti itu.
Cover yang dipermasalahkanBaru saja sehari terpajang di toko-toko buku, tiba-tiba Toko Buku Gramedia menarik seluruh buku Tilogi Lekra Tak Membakar Buku dan mengembalikan pada penerbitnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Usut punya usut ternyata mereka khawatir dengan cover buku “Lekra Tak Membakar Buku” yang memuat gambar ‘palu arit’ yang merupakan lambang PKI. Mereka tampaknya khawatir karena pelarangan logo PKI hingga kini belum dicabut oleh pemerintah. Karenanya TB Gramedia bersikukuh tak mau memajang buku ini jika covernya belum diganti.
Sebenarnya lambang PKI pada buku ini tak terlalu kentara karena hanya berupa gambar timbul (embossed) tanpa bingkai dan warna, nyaris tak terlihat terutama dari jarak jauh. Sehingga sekilas yang terlihat hanyalah cover putih polos dengan judul buku berwarna merah di bagian bawahnya.
Sebenarnya desain cover seperti ini menggambarkan keberadaan Lekra dengan PKI. Lekra bukanlah salah satu organ PKI, tapi tokoh-tokoh Lekra adalah orang-orang yang juga tergabung dalam PKI. Jadi dibilang PKI bukan, dibilang bukan PKI juga salah.
Awalnya penerbit maupun penulisnya tetap ingin mempertahankan cover tersebut, namun tampaknya daripada buku ini tersendat peredaraannya dan di sweeping oleh pihak-pihak tertentu sehingga kesempatan masyarakat untuk membaca buku ini menjadi terhalang, akhirnya diambil jalan kompromi. Daripada membuang-buang waktu dan dana untuk mengganti cover baru, maka ditutuplah lambang palu aritnya dengan kertas putih.
Akhirnya buku monumental ini kini tersaji dengan wajah yang tambal sulam, hal yang buruk dan tak memenuhi kaidah estetika sebuah buku….
@h_tanzil

 Jenghis Khan membuatku mengerti sejarah mengenai sang penakluk lagendaris, tampaknya penulis buku ini tidak hanya menulis buku berdasarkan riset pustaka semata melainkan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya langsung ke tempat-tempat Jenghis Khan pernah hidup.
Jenghis Khan membuatku mengerti sejarah mengenai sang penakluk lagendaris, tampaknya penulis buku ini tidak hanya menulis buku berdasarkan riset pustaka semata melainkan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya langsung ke tempat-tempat Jenghis Khan pernah hidup.